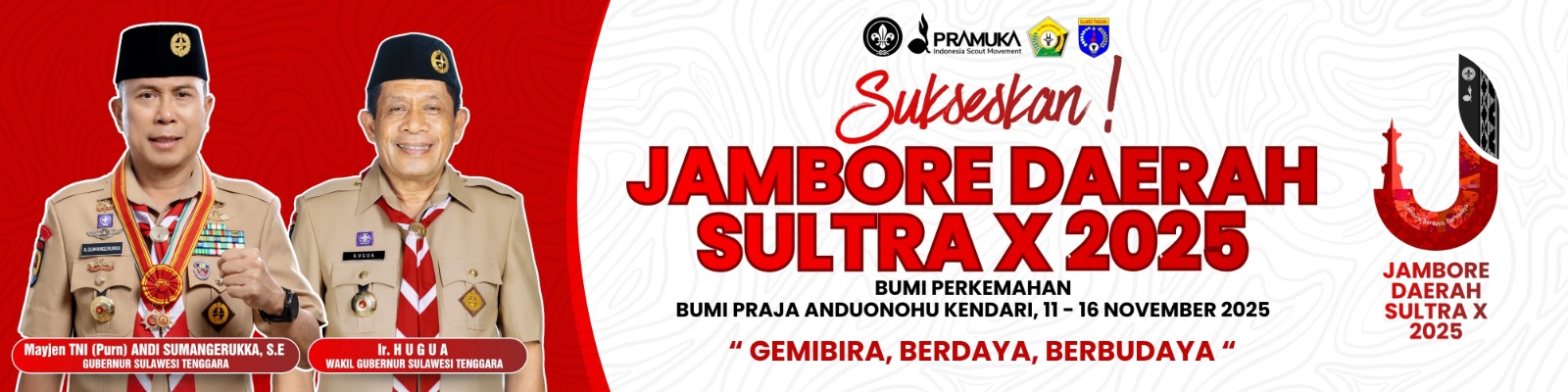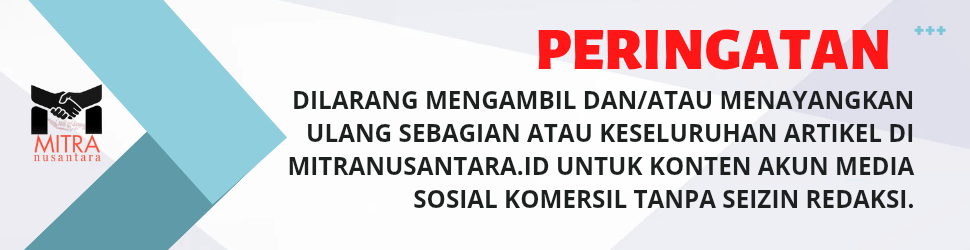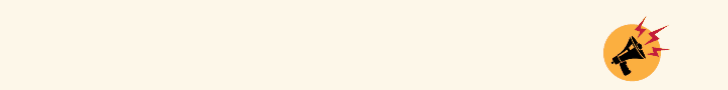Oleh: Novrizal R Topa
MITRANUSANTARA.ID – Perkebunan kelapa sawit kerap menjadi perbincangan yang penuh dinamika di ruang publik. Di satu sisi, ia dituding sebagai penyebab deforestasi dan kerusakan lingkungan. Namun di sisi lain, kehadirannya di sejumlah wilayah pedesaan justru menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
Industri kelapa sawit telah lama menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Selain menjadi komoditas ekspor unggulan dengan nilai mencapai USD 38,2 miliar pada tahun 2023 (data GAPKI), industri ini juga memainkan peran vital dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya terisolasi dari akses pembangunan.
Dari sudut pandang ekonomi lokal, kehadiran perusahaan sawit telah membuka ribuan lapangan pekerjaan. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada pertanian subsisten atau perkebunan di mana petani hanya menanam tanaman yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri dan keluarga mereka, dengan sedikit atau tanpa sisa untuk dijual. Namun kini memiliki alternatif pendapatan yang lebih stabil sebagai buruh kebun, pemanen, hingga staf administrasi. Upah yang diterima tiap bulan menjadi sumber perputaran uang di desa-desa yang sebelumnya stagnan.
Selain itu, di balik statistik makro tersebut, terdapat realitas yang tak kalah penting untuk dibicarakan: bagaimana sawit mengubah wajah ekonomi masyarakat sekitar perkebunan, dan bagaimana kita menakar manfaat serta tantangan yang ditimbulkannya secara seimbang
Data dari BAPPENAS menyebutkan bahwa sektor sawit menyerap sekitar 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung di seluruh Indonesia. Jumlah ini tidak hanya mencerminkan skala besar industri ini, tapi juga pentingnya sawit sebagai penyerap tenaga kerja di pedesaan.
Lebih dari sekadar menjadi pekerja, masyarakat juga turut mengambil peran dalam rantai ekonomi melalui kegiatan usaha mikro. Warung makan, toko sembako, jasa transportasi, hingga usaha kos-kosan mulai tumbuh seiring kebutuhan tenaga kerja sawit. Inilah bentuk ekonomi kerakyatan yang tercipta dari sebuah ekosistem industri berbasis lahan.
Di banyak daerah seperti Rokan Hulu (Riau), Seruyan (Kalteng), hingga Mamuju (Sulbar), masyarakat yang sebelumnya hidup dari ladang berpindah ke kebun sawit. Mereka bekerja sebagai pemanen, perawat tanaman, sopir angkut, staf administrasi, bahkan teknisi pabrik pengolahan. Upah tetap bulanan dan bonus produksi menjadi daya tarik utama. Ekonomi lokal pun ikut menggeliat karena uang berputar di warung, bengkel, jasa transportasi, dan pasar-pasar desa.
Disisi lain, sebagian perusahaan sawit juga menerapkan sistem kemitraan plasma dengan petani lokal. Melalui skema ini, masyarakat diberi lahan dan fasilitas produksi, sementara perusahaan bertindak sebagai pembina dan penjamin hasil. Ketika dilakukan secara transparan dan berkeadilan, model ini terbukti mampu meningkatkan taraf hidup petani. Mereka bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek yang aktif dalam roda ekonomi.
Sebagai contoh, harga TBS plasma di Provinsi Riau pada akhir 2024 tembus angka Rp 3.675,66/kg – tertinggi dalam sejarah. Hal ini membuktikan bahwa sawit dapat menjadi sumber kesejahteraan apabila dikelola secara profesional dan transparan.
Tak dapat dipungkiri, kehadiran perusahaan turut membawa pembangunan infrastruktur. Jalan-jalan desa yang dahulu rusak mulai diperbaiki, akses listrik dan air bersih semakin luas, bahkan fasilitas pendidikan dan kesehatan turut dikembangkan lewat program tanggung jawab sosial (CSR). Ini menandai bahwa pembangunan ekonomi sejati tidak hanya berbicara soal uang, tetapi juga kualitas hidup.
Studi dari BPDPKS mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir, lebih dari 1.200 desa di sekitar perkebunan sawit mengalami peningkatan akses layanan dasar secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa kehadiran sawit tak sekadar membawa hasil panen, tapi juga memperbaiki kualitas hidup warga.
Meski demikian, tantangan masih ada. Konflik lahan, ketimpangan hasil, hingga keluhan soal upah dan lingkungan tetap menjadi catatan kritis yang tidak boleh diabaikan. Di sinilah pentingnya sinergi antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah dalam membangun sistem pengawasan dan dialog yang sehat.
Melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024, pemerintah memperkuat regulasi kemitraan sawit. Tujuannya untuk menjamin keadilan dalam pembagian keuntungan, transparansi harga, dan kepastian hukum bagi petani plasma.
Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak bisa berjalan sendiri. Perusahaan sawit dituntut untuk lebih bertanggung jawab, masyarakat harus aktif menyuarakan haknya, dan pemerintah wajib hadir sebagai pengatur arah kebijakan yang adil. Jika kolaborasi ini terwujud, maka industri sawit bukan hanya menjadi sumber devisa negara, tetapi juga menjadi tulang punggung kesejahteraan rakyat di akar rumput.
Sawit seharusnya tidak hanya meninggalkan jejak kaki di tanah, tetapi juga jejak harapan di hati masyarakat.
(Penulis adalah eks Karyawan PT Hindoli a Cargill Company, Perusahaan Kelapa Sawit di sei Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tahun 1997-2002).