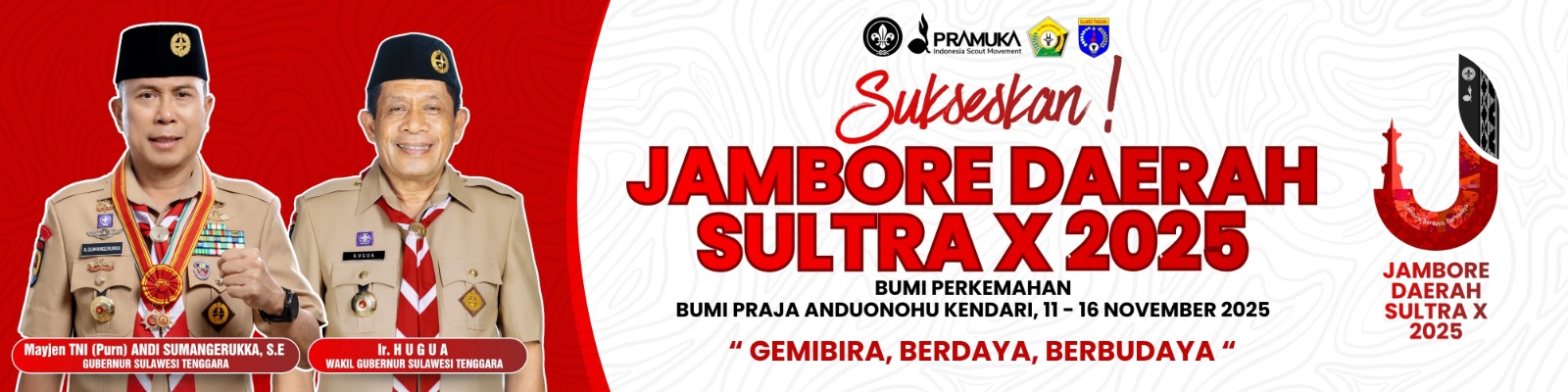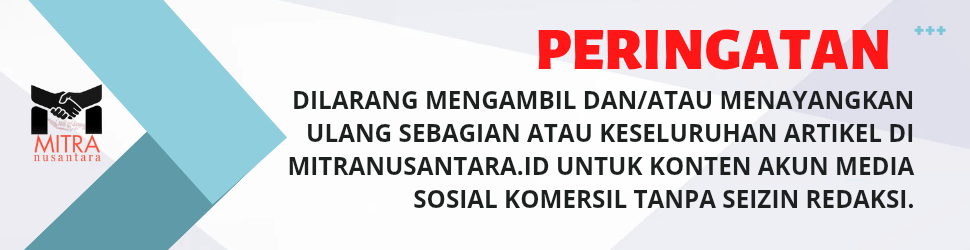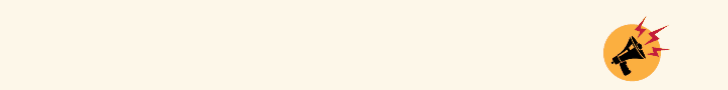Oleh: Tomy Almijun Kibu
Mahasiswa Pasca Sarjana Program Magister Administrasi Pembangunan, UHO
“Seni dalam dimensi ekologis bukan lagi semata estetika, tetapi menjadi wacana kritik, advokasi, dan tanggung jawab sosial yang mendalam. Kecenderungan ini muncul dari kebutuhan manusia untuk membangun kesadaran kolektif atas krisis lingkungan yang semakin akut.”
— Mayang Anggrian & Nur Iksan, dalam artikelnya tentang seni dan advokasi isu lingkungan, jurnal.isi-ska.ac.id
Kutipan di atas mempertegas bahwa seni tidak berada di luar persoalan sosial dan ekologis. Ia menjadi medium ekspresi yang tidak hanya memproduksi bentuk dan keindahan, tetapi juga menggali makna dan konsekuensi hubungan antara manusia dan alam. Ketika krisis lingkungan semakin nyata—bukan sekadar wacana ilmiah, tetapi pengalaman hidup masyarakat—seni harus mampu menjembatani kesadaran, rasa, dan tindakan.
Bagaimana Seni Harus Bersikap pada Kerusakan Lingkungan?
Seni sering dipahami sebagai ruang otonom: bebas nilai, bebas kepentingan, dan terpisah dari realitas sosial. Namun, pendekatan ini menjadi problematik ketika seni berhadapan dengan krisis ekologis. Kerusakan lingkungan bukanlah peristiwa netral; ia lahir dari relasi kuasa antara modal, negara, dan masyarakat. Oleh karena itu, seni yang memilih bersikap “netral” sesungguhnya sedang berpihak pada dominasi yang ada.
Seni, dalam konteks ekologis, harus berpindah dari sekadar representasi menuju keberpihakan. Keberpihakan ini bukan berarti propaganda dangkal, melainkan kesadaran bahwa setiap praktik artistik berada dalam jaringan sosial, ekonomi, dan ekologis tertentu. Seni harus mampu mengungkap relasi sebab-akibat antara pembangunan eksploitatif dan penderitaan ekologis masyarakat.
Penelitian Anggrian dan Iksan menunjukkan bahwa seni ekologis bekerja sebagai ruang refleksi sosial yang memungkinkan publik memahami krisis lingkungan bukan hanya sebagai peristiwa alam, tetapi sebagai akibat dari kebijakan dan tindakan manusia. Dengan demikian, seni menjadi medium pedagogis—mengajarkan cara melihat dunia secara lebih ekologis dan berkelanjutan.
Bagaimana Seni Bisa Menjadi Senjata untuk Melawan Kerusakan Lingkungan?
Berbeda dengan senjata fisik atau instrumen hukum, seni bekerja pada ranah kesadaran, emosi, dan imajinasi kolektif. Di sinilah letak kekuatannya. Seni mampu menyentuh lapisan psikologis yang sering tidak dijangkau oleh laporan ilmiah atau wacana kebijakan publik.
Seni berfungsi sebagai senjata kultural dalam tiga lapisan utama.
Pertama, seni mengonkretkan krisis lingkungan. Perubahan iklim, degradasi ekosistem, atau banjir ekologis sering hadir dalam bentuk angka dan grafik yang abstrak. Seni mengubahnya menjadi pengalaman inderawi—visual, suara, dan ruang—yang dapat dirasakan secara langsung oleh publik.
Kedua, seni menciptakan gangguan (disruption) terhadap narasi dominan. Seni instalasi dari limbah, mural kritik di ruang publik, atau pertunjukan performatif di lokasi terdampak kerusakan lingkungan mematahkan narasi pembangunan yang sering dipresentasikan sebagai kemajuan tanpa korban.
Ketiga, seni mampu memobilisasi solidaritas. Praktik seni berbasis komunitas memungkinkan warga terdampak terlibat langsung dalam proses kreatif, menjadikan seni bukan milik seniman semata, tetapi milik kolektif sosial yang sedang berjuang mempertahankan ruang hidupnya.
Studi tentang artivism menunjukkan bahwa seni dapat berkontribusi pada transformasi keberlanjutan melalui perubahan cara berpikir, perubahan perilaku, dan bahkan tekanan terhadap kebijakan publik. Dengan demikian, seni bukan sekadar simbol perlawanan, tetapi bagian dari strategi perubahan sosial.
Dilema Etis Seniman: Antara Nafkah dan Integritas Ekologis
Salah satu persoalan paling kompleks dalam seni ekologis adalah posisi seniman dalam struktur ekonomi. Seniman tidak hidup di ruang hampa; mereka bergantung pada sistem produksi budaya yang sering kali dibiayai oleh korporasi. Ironisnya, banyak korporasi tersebut merupakan aktor utama perusakan lingkungan.
Di sinilah muncul dilema etis: apakah seniman harus menerima kerja dari korporasi perusak lingkungan demi keberlangsungan hidup, atau mempertahankan integritas ekologis dengan risiko keterpinggiran ekonomi?
Secara akademik, dilema ini tidak bisa dibaca secara hitam-putih. Namun, penting ditegaskan bahwa seni yang terlibat dalam praktik greenwashing—memoles citra ramah lingkungan tanpa perubahan nyata—telah kehilangan fungsi kritisnya. Seni semacam ini justru menjadi alat ideologis yang menormalkan kerusakan ekologis.
Pilihan etis yang dapat ditempuh seniman adalah membangun otonomi kreatif melalui kerja kolektif, kolaborasi komunitas, atau model pendanaan alternatif. Dengan cara ini, seniman tetap dapat bertahan secara ekonomi tanpa harus mengorbankan keberpihakan ekologisnya. Dalam konteks ini, seniman berfungsi sebagai intelektual publik, bukan sekadar produsen estetika.
Contoh Seni dan Sikap terhadap Banjir Ekologis di Sumatra
Persoalan banjir di Sumatra—terutama di Sumatra Selatan, Jambi, Riau, dan Sumatra Barat—tidak hanya menjadi isu ekologis, tetapi juga medan refleksi kultural. Sejumlah seniman dan karya seni Indonesia telah menjadikan banjir sebagai bahasa kritik atas relasi timpang antara manusia, alam, dan kekuasaan.
“Siklus: Seni di Atas Galon”
Cornelia Agatha & Seniman IKJ
Sebuah aksi seni lintas media bertajuk “Siklus” yang digagas oleh Cornelia Agatha bersama seniman dari Institut Kesenian Jakarta (IKJ) menyikapi banjir di Sumatra dan digelar kembali pada 19 Desember 2025.
(https://h7.cl/1lFWj)
Karya ini mengangkat pesan ekologis tentang sungai sebagai urat nadi kehidupan dan bahaya kerusakan lingkungan yang memicu banjir. Pertunjukan bersifat site-specific (dirancang untuk tempat tertentu) dan menggunakan media ekspresif lintas disiplin seni untuk menyuarakan kritik terhadap kerusakan ekologis sekaligus empati terhadap warga terdampak banjir.
Fotografi Dokumenter Lingkungan di Riau dan Jambi
Sejumlah fotografer dokumenter independen dan jurnalis visual di Riau dan Jambi menjadikan banjir tahunan sebagai proyek seni-dokumentasi. Melalui foto rumah terendam, anak-anak bermain di genangan, hingga lanskap hutan gundul di hulu sungai, karya-karya ini menempatkan banjir sebagai realitas keseharian yang dinormalisasi oleh negara dan korporasi.
Fotografi di sini bekerja di wilayah antara seni dan jurnalisme—menghadirkan empati sekaligus gugatan visual terhadap narasi “bencana alam” yang menutupi akar masalah.
Pada akhirnya, seni melawan banjir bukan tentang siapa yang paling lantang, tetapi siapa yang berani tidak lupa. Karena selama banjir terus dianggap biasa, selama seni memilih diam, maka yang tenggelam bukan hanya rumah-rumah warga, tetapi juga rasa keadilan kita bersama.